Menurut penelitian Taufiq Ismail untuk bacaan buku-buku karya sastra yang dilakukan di seluruh dunia,
Penerbit itu juga mengatakan bahwa, “Musuh utama buku di kalangan mahasiswa sekarang adalah PULSA. Dalam satu minggu mereka bisa menghabiskan pulsa hingga hitungan angka 100 ribu rupiah, yang mungkin jika dikira-kira jumlah itu minimal dapat dibelikan 3 buku. Artinya, dalam 1 bulan mereka sesungguhnya bisa membeli 12 buku”.
Penerbit itu sesungguhnya teramat geram dengan kondisi kebanyakan mahasiswa kita sekarang. Tapi apa mau dikata? Kenyataannya, setiap tahun puluhan ribu sarjana baru tiba-tiba linglung dan menganggur, menjadi beban baru bagi Negara yang sesungguhnya sudah mengurus mereka dengan baik melalui subsidi pendidikan (dalam bentuk fasilitas, gaji dosen dan pegawai, dll) yang tak kurang dari 2 juta rupiah setiap semesternya. Tapi apa yang didapat negara dari subsidi itu, kecuali beban pengangguran yang semakin bertambah?
Menurut penerbit itu, saat ini
Kemudian penerbit itu kembali menekuk wajahnya karena teringat kembali sebuah kisah ketika ia berdialog dengan seorang mahasiswa, yang kemudian diajukan sebuah pertanyaan kepadanya, “Apakah engkau tidak pernah merasa bahwa subsidi pendidikan yang diberikan Negara untuk kelancaran kuliahmu adalah sebuah amanah? Amanah dari rakyat, amanah dari keringat serta penderitaan mereka, karena subsidi itu berasal dari pajak. Pajak yang dibayarkan dari pedagang sayur di pasar, dari tukang becak yang membeli indomie misalnya, dari seorang buruh yang membeli rokok, dari pengemis, dari penjudi, dari pemabuk. Mereka semua menyimpan harapan bahwa kelak, engkau sebagai seorang mahasiswa akan membangun bangsa ini menjadi lebih baik, karena mereka percaya bahwa engkau adalah kaum terdidik. Lalu bagaimana mungkin engkau bisa menghamburkan waktumu dengan sibuk berjam-jam setiap hari berhalo-halo menghamburkan uang bersama pacar-pacarmu, merusak komputermu dengan gambar-gambar dari VCD bajakan, begadang hanya untuk berhura-hura di kafe hingga engkau pulang larut malam untuk kemudian siang harinya engkau mengantuk? Apakah engkau tahu bahwa mengkhianati amanah jutaan rakyat adalah sebuah dosa, yang kelak akan engkau pertanggungjawabkan dengan berat dihadapan Tuhanmu?
Tetapi sesaat kemudian penerbit itu kembali tersenyum dan bernafas lega karena ia teringat dengan sekelompok kecil mahasiswa yang masih bertanggungjawab terhadap beban yang (terutama) dititipkan orangtua mereka. Yaitu mereka yang masih terlihat bergerombol di perpustakaan, mereka yang dengan jujur mengerjakan ujian tanpa mencotek, mereka yang sedang rapat di sebuah ruangan organisasi, mereka yang masih terlihat sabar memilih-milih judul di toko buku, mereka yang pantas dibanggakan yakni ketika negara melakukan kesalahan dan mereka bergerombol merapatkan barisan untuk mengingatkan.
Begitulah kira-kira uneg-uneg salah seorang penerbit mengenai kondisi kita, mahasiswa… semoga kita mampu menjadi sosok-sosok mahasiswa yang tidak hanya bertanggungjawab terhadap amanah, tapi juga mampu dibanggakan oleh bangsa
“Kecerdasan adalah abstraksi kepribadian dalam memandang dan menghayati kehidupan…”



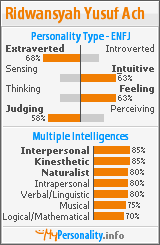


1 komentar:
Ehyaaa.. Saya tidak sampai kepikiran sejauh itu sampai kepada pengmis, pemabuk, dll, dn syyakin merekapun tdk berpikir sejauh itu., tp., amanah tetap amanh., mksh telah di ingatkan., :D
Posting Komentar